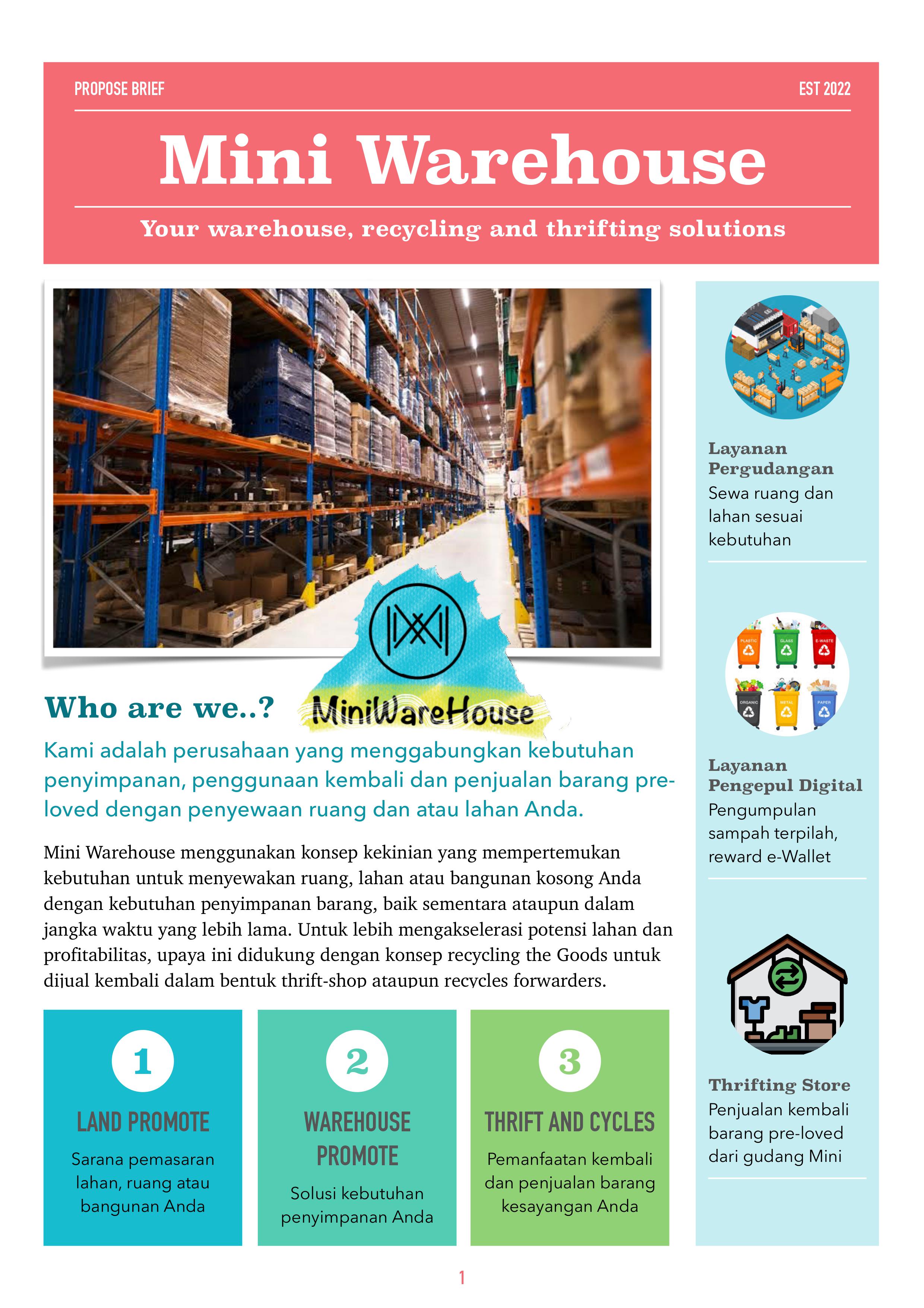tinjauan filosofis pendidikan sebagai hak dasar
tinjauan filosofis pendidikan sebagai hak dasar
Jul 08, 2025
32
pendidikan gratis, tonggak hak asasi dan masa depan inklusif pendidikan indonesia
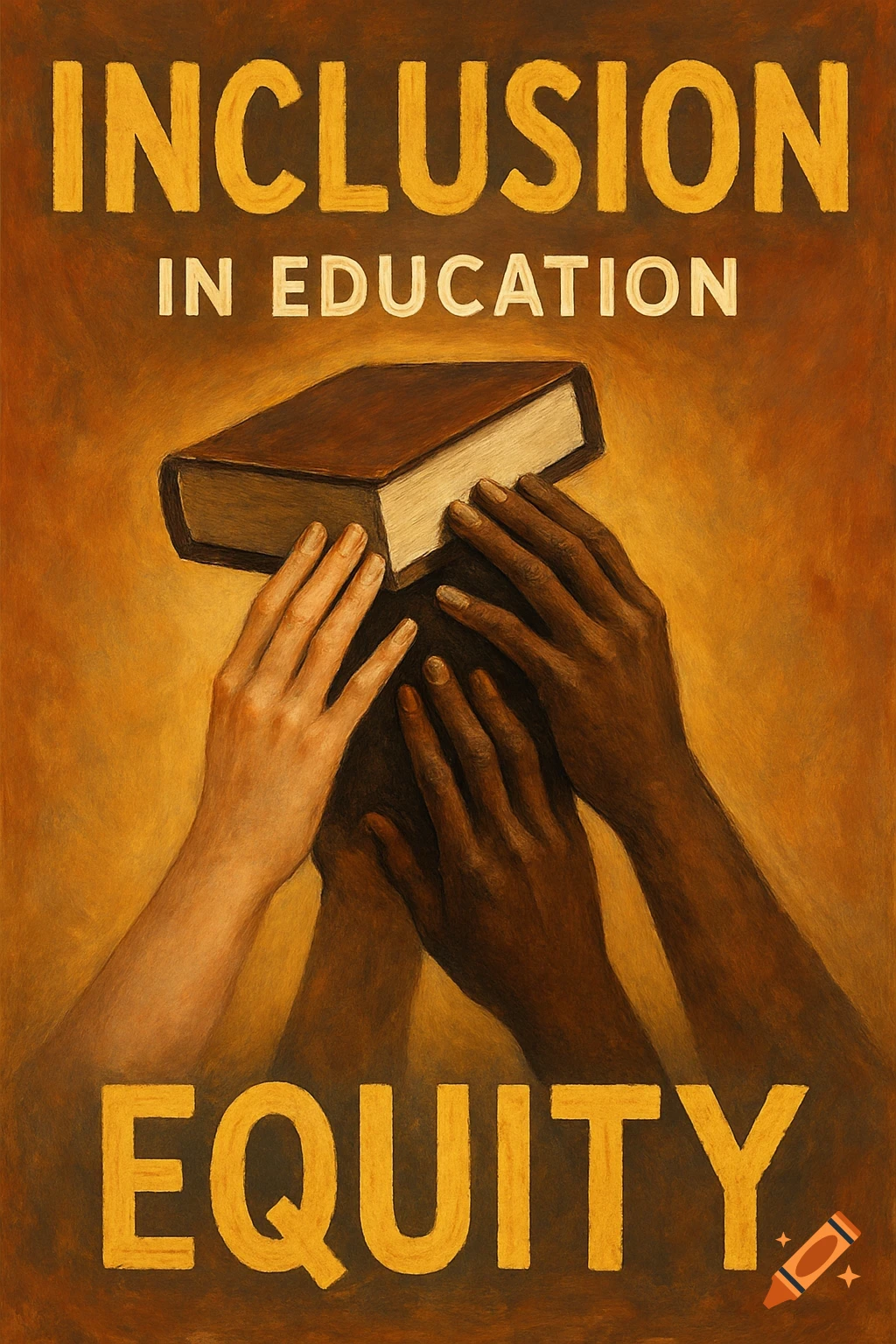
Pasal 28 C dan 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks Internasional, Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menyatakan bahwa Pendidikan dasar harus gratis dan wajib. Pendidikan merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang menuntut negara untuk melakukan pemenuhan secara progresif. Namun upaya Indonesia mewujudkan amanat tersebut masih menghadapi jalan terjal dan berliku. Dalam praktek sehari-hari, upaya untuk mengakses pendidikan secara inklusif dan terbuka justru berubah menjadi praktek kompetisi yang berujung komersialisasi dan bisnis yang melahirkan eksklusivitas. Sistem penerimaan siswa baru di sekolah negeri, dalam format dan tingkatan pendidikan apapun, pada pelaksanaannya selalu menyisakan permasalahan dan catatan perbaikan kebijakan menyeluruh karena hampir selalu melahirkan praktek penyimpangan seperti jual beli kursi, perubahan domisili calon siswa, hingga pengaturan rangking “daftar jadi” calon siswa baru.
Sejatinya, pendidikan sebagai hak asasi manusia tidak hanya bermakna sebagai kewajiban negara untuk menyediakan, tetapi juga mencerminkan martabat manusia itu sendiri. Dalam pandangan John Dewey, pendidikan bukan hanya alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi jalan untuk membentuk warga negara yang berdaya nalar, kritis dan etis. Maka pengabaian terhadap keadilan akses pendidikan adalah pengabaian terhadap demokrasi itu sendiri. John Dewey (1859 -1952) seorang filsuf, psikolog dan pendidik asal Amerika yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam teori pendidikan. Dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran pragmatisme dan pelopor pengembangan pendidikan progresif. Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sosial dinamis yang bertujuan menyiapkan individu dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Menurut Dewey, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, namun juga membentuk karakter dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sosial budaya. Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education (1916), Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses kehidupan, bukan persiapan untuk hidup di masa depan. Karenanya, ia menganggap bahwa sekolah harus berfungsi sebagai mikrokosmos dari masyarakat dimana siswa belajar dan mengembangkan keterampilan sosial serta berpikir kritis yang diperlukan dalam partisipasi aktif kehidupan bermasyarakat. Dewey juga berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dan inklusif. Melalui pendidikan yang baik, seseorang dapat belajar untuk bekerjasama menyelesaikan masalah secara kreatif dan memahami serta menghargai perbedaan dalam masyarakat.
Paulo Freire (1970) juga memiliki pandangan yang sejalan, bahwa pendidikan seharusnya bersifat dialogis, membebaskan dan transformatif. Ketika seorang anak dari keluarga tidak mampu dipaksa keluar dari sekolah karena biaya, maka yang dicabut bukan hanya akses belajar, tetapi juga martabat dan masa depannya. Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf asal Brazil, dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan teori pendidikan kritis. Freire berfokus pada hubungan antara pendidikan dan ketidaksetaraan sosial serta penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang tertindas. Pemikiran Freire relevan dalam konteks perkembangan masyarakat, terutama dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan ekonomi pada banyak negara berkembang, termasuk Brazil yang merupakan tanah kelahirannya. Pendidikan dialogis dalam pandangan Freire, mengutamakan interaksi aktif antara guru dan siswa, bukan berarti satu arah sebagaimana model pendidikan tradisional Dimana guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Dialog dan kolaborasi adalah kunci dalam proses pendidikan. Dalam bukunya, Pedagogy of The Oppressed (1970), Freire menulis bahwa pendidikan, untuk menjadi benar-benar edukatif, harus berbasis pada dialog yang penuh kesetaraan, bukan pada hubungan penuh kekuasaan. Bagi Freire, pendidikan adalah alat untuk menciptakan kesadaran kritis, kemampuan untuk melihat dan memahami ketidakadilan dalam Masyarakat dan berusaha untuk mengubahnya. Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu untuk beradaptasi dengan masyarakat yang ada tetapi juga berperan aktif dalam mengubahnya. Menurut Freire, pendidikan harus mampu mengatasi ketimpangan sosial dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Ia percaya bahwa pendidikan yang efektif adalah yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi dan membentuk dunia mereka sendiri melalui pemahaman kritis terhadap realitas sosial, budaya dan politik yang dihadapi. Dalam konteks inilah, putusan MK merupakan upaya mengembalikan posisi pendidikan sebagai hak, bukan komoditas.
Lebih lanjut untuk memahami dinamika pendidikan dalam perkembangan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan manusia, Amartya Sen menawarkan teori Capability Approach yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Martha Nussbaum. Capability Approach menekankan pada kemampuan individu untuk mencapai berbagai fungsi atau kegiatan yang mereka anggap berharga dalam hidup mereka. Pendekatan ini menawarkan perspektif alternatif terhadap pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada pengukuran kemiskinan atau kesejahteraan melalui indikator ekonomi seperti pendapatan atau konsumsi. Amartya Sen adalah seorang ekonom dan filsuf asal India yang pertama kali mengemukakan teori Capability Approach pada 1980-an. Dalam pandangan Sen, kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dengan standar material seperti pendapatan atau konsumsi, tetapi lebih pada apa yang individu mampu lakukan dan capai dalam hidup mereka. Sen mengidentifikasi dua konsep utama dalam pendekatannya, functioning dan capabilities. Functioning merujuk pada berbagai aktivitas atau keadaan yang dicapai oleh seseorang, sementara capabilities adalah kebebasan atau kemampuan seseorang untuk memilih dan mencapai functioning yang mereka nilai penting. Teori Sen menekankan pada pentingnya kebebasan substantif yang mengacu pada kemampuan individu untuk hidup sesuai dengan pilihan mereka tanpa dibatasi oleh hambatan sosial atau ekonomi. Sen juga menyoroti pentingnya keadilan sosial yang dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang setara untuk mencapai fungsi yang mereka anggap penting dalam hidup mereka.
Martha Nussbaum, seorang filsuf Amerika, mengembangkan lebih lanjut Capability Approach milik Sen, terutama dengan memberikan daftar fungsi dasar yang dianggap penting bagi setiap individu untuk menjalani hidup yang bermartabat. Nussbaum memperkenalkan daftar kapasitas dasar yang meliputi fungsi seperti hidup yang panjang, menjaga kesehatan fisik, emosi yang stabil, kemampuan untuk berpikir dan merencanakan kehidupan serrta partisipasi dalam kehidupan sosial. Nussbaum berpendapat bahwa kemampuan dasar ini harus dijamin oleh negara untuk memastikan setiap individu dapat mencapai kehidupan yang bermartabat. Teori Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum memiliki hubungan yang sanagt erat dengan pendidikan dan pemenuhan hak dasar. Kedua teori ini mengajukan pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam membangun kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, serta berfungsi sebagai alat untuk pemenuhan hak dasar. Menurut teori Capability Approach, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi materi, seperti pendapatan atau konsumsi, namun lebih pada kemampuan individu untuk mencapai berbagai fungsi dalam hidup mereka yang mereka anggap berharga. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kemampuan ini. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak dasar, teori Capability Approach menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
Pendidikan dianggap sebagai salah satu komponen utama yang memungkinkan individu untuk mengakses kemampuan dasar yang mereka butuhkan untuk hidup bermartabat. Oleh karena itu pendidikan bukan hanya alat untuk mempersiapkan idividu untuk dunia kerja, tetapi juga untuk mencapai fungsi dasar yang dibutuhkan untuk hidup yang sehat, aman, dan terpenuhi. Pendidikan yang berbasis pada Capability Approach juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang terpinggirkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Teori ini berargumen bahwa pendidikan harus lebih dari sekedar instrumen untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan teknis, bahwa pendidikan harus membantu individu untuk mengidentifikasi dan menanggapi ketidakadilan yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Quotes.
"kebajikan timbul dari haus akan ketidaktahuan, kesombongan lahir atas kekenyangan sok tahu."- myself
"orang besar membicarakan ide, orang kecil membicarakan orang lain."- habib husein jafar
"terkenal tidak sama dengan jadi punya banyak buyer."- pandji pragiwaksono
"your are the best on what you are believe, not the article tells."- myself
"dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal."- habib husein jafar

loading ...